Mimikri Representasi dalam Roman Larasati
Teori Post-Kolonialisme
Secara etimologis postkolonial
berasal dari kata ‘post’ dan kolonal, sedangkan kata kolonial itu sendiri
berasal dari akar kata colonia. Bahasa romawi. Yang berarti tanah pertanian
atau tanah pemukiman. Teori postkolonial pada awalnya dimulai ketika adanya
kesusastraan persemakmuran yang mencoba mengkaji mengenai efek dari
kolonialisasi yang dilakukan oleh Inggris.
Pada perkembangan selanjutnya,
sebuah tulisan dari Edward Said yang berjudul Orientalism yang mengangkat
mengenai wacana-wacana kolonial yang sangat menghegemoni dunia timur. Dalam
pandangan Said(1978: 5), keberadaan Timur bukan begitu saja didapatkan sebagai
Timur, tetepai timur memang ditimurkan oleh Barat melalui
pengetahuan-pengetahuannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan-pandangan
yang mengeksiskan teori postkolonialisme adalah Gayatri C. Spivak melalui
tulisan Can The Subaltern Speak? Yang memandang bahwa kemerdekaan sebuah negera
masih memposisikan kelas Subaltern sebagai bayang-bayang saja. Para petani,
kaum buruh, dan perempuan masih tetap menikmati dirinya sebagai kaum yang tidak
dapat bersuara.
Dalam
penerapannya, teori sastra memiliki berbagai macam teori yang dapat
dipergunakan untuk menganalisis teks-teks karya sastra. Begitu banyaknya macam
teori tersebut sehingga dapat kita bagi menjadi dua bagian yakni teori-teori
yang berada pada zaman sebelum modernisme dan sesudah modernisme. Dalam teori
sastra kedua ini, teori yang dipergunakan untuk menganalisis adalah teori yang
berada pada zaman pasca-modernisme. Salah satu teori yang akan dipergunakan
untuk menganalisis teks sastra kali ini adalah teori post-kolonial.
Teori post-kolonial itu sendiri ialah
cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti:
sejarah, politik, ekonomi, sastra dan berbagai dokumen lainnya, yang terjadi di
negara-negara bekas koloni Eropa modern. (Ratna, 2008:90). Istilah
post-kolonial ini sendiri tidak lagi merujuk kepada negaranya tetapi kepada
kondisi yang telah ditinggalkan terhadap negara tersebut sehingga kajian ini
tidak hanya membahas di permukannya saja tetapi hingga ke dalam, yakni sisi psikisnya.
Berkaitan dengan paragraf diatas, maka gejala-gejala
kultural tersebut dapat ditemukan pada berbagai negara seperti Afrika,
Australia, Bangladesh, Canada, Karibia, India, Malaysia dan Indonesia. Maka
karya-karya sastra di Indonesia tentu berkaitan dengan teori post-kolonial
tersebut. Dimana akan banyak ditemukan relasi antara penjajah dan terjajah pada
karya sastra yang dihasilkan para penulis di Indonesia. Misalnya seperti novel Salah Asuhan karya Abdoel Moeis dan Layar Terkembang karya Sutan Takdir
Alisjahbana.
Dalam
makalah ini, penulis menggunakan novel Larasati
karya Pramoedya Ananta Toer sebagai objek teks yang akan dibedah lebih
mendalam. Sebagai sebuah teori, post-kolonial merupakan sebuah teori yang
objeknya merupakan teks yang menunjukkan keadaan psikis dari para bangsa yang
terjajah. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang menjadi korban jajahan,
terutama oleh Belanda. Lamanya penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap
Indonesia merupakan sebuah kajian menarik dimana posisi Belanda sebagai
penjajah yang pernah menginjakkan kaki selama tiga setengah abad di Indonesia,
mempengaruhi psikis dari bangsa Indonesia. Terpengaruhnya psikis bangsa
Indonesia inilah dapat kita temui dalam beberapa tokoh yang terdapat dalam
novel ini. Dimana tokoh-tokoh dalam novel ini identik dengan pertanda yang
cukup lekat dengan post-kolonialisme yaitu mimikri.
Sinopsis Larasati
Larasati
merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seorang wanita yang berprofesi
sebagai aktris pada zaman pemerintahan kolonial Belanda bernama Larasati.
Sebagai seorang aktris, Larasati memiliki paras yang cantik. Kecantikan serta
profesinya membuatnya terkenal di kalangan-kalangan orang-orang dengan jabatan
yang cukup penting pada kala itu. Suatu waktu, dirasa sudah terlalu lama
meninggalkan ibunya, Larasati berpikir untuk pulang kembali padanya.
Berdomisili di Yogyakarta, ia rela meninggalkan lelaki yang ia cintai bernama
Kapten Oding demi menemui ibunya yang berada di Jakarta.
Dalam
perjalanannya menuju Jakarta, ia bertemu dengan kenalannya yakni Mardjohan dan
Kolonel Surjo Sentono. Tawaran menggiurkan pun datang dari mereka berdua, Ara
diajak kembali untuk bermain film. Mengingat Mardjohan dan Kolonel Surjo
Sentono adalah seseorang yang berpihak kepada Belanda, Ara menolak
mentah-mentah tawaran tersebut. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa film
tersebut merupakan film propaganda Belanda. Ketidaksukaan Ara terhadap kolonial
ini tertangkap oleh supir dari Kolonel Surjo Sentono yang ternyata seorang
pejuang. Dengan mobil yang dibawanya, supir kolonel ini akhirnya membantu
mengantarkan Ara ke tempat ibunya tinggal.
Sebagai
balas budi terhadap supir Kolonel Sentono yang belakangan diketahui bernama
Martabat, Ara membantunya menuju pedalaman untuk bertemu dengan teman-teman
pejuang yang lain. Selama perjalanan menuju ke rumah ibunya, Ara bertemu dengan
banyak sekali pejuang. Baik itu mereka yang masih anak-anak, pemuda bahkan
hingga kakek nenek masih saja berjuang demi kemerdekaan Indonesia.
Pertemuan-pertemuan itulah yang membuat perasaan tak suka Ara kepada Ara
semakin kuat dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pejuang. Pengalaman
yang paling diingat oleh Ara adalah ketika ia dan Martabat ikut turun berperang
dengan Belanda bersama pemuda di tempat ibunya tinggal demi membuktikan bahwa
ia bukan utusan dari NICA.
Ibu
Ara yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga berketurunan
Arab. Ia memiliki seorang majikan bernama Jusman yang pada akhirnya jatuh cinta
akan kecantikan Ara. Ara pun dipaksa untuk tinggal satu kamar oleh Jusman tanpa
menikah. Jusman sendiri walaupun berketurunan Arab, ia memihak Belanda dengan
tugas ia harus memberangus orang-orang yang berani memberontak kepada Belanda.
Hingga akhirnya ketika Belanda kalah dan Jusman mau tak mau harus meninggalkan
Indonesia, Ara dan ibunya pun terbebas dari kekangan Jusman. Tak lama, ia
bertemu kembali dan menikah dengan lelaki yang dicintainya, yakni Kapten Oding.
Representasi
Mimikri pada Dua Tokoh dalam Larasati
Dalam
mengenali post-kolonialisme dalam suatu karya sastra, kita dibantu dengan
beberapa istilah yang lekat dengan post-kolonialisme. Berbagai macam istilah
yang berdekatan dengan post-kolonialisme itu sendiri salah satunya adalah
mimikri. Mimikri merupakan sebuah upaya masyarakat atau kelompok lokal yang
meniru atau mengimitasi kebudayaan modern yang ditempilkan dalam gaya
berbicara, berpakaian, bersikap, dan citra budaya lainnya. Upaya ini dilakukan
oleh kelompok lokal ataupun sublatern agar mendapatkan akses yang sama dengan
yang memiliki kekuasaan.
Bila
kita melihat karya yang ditulis Pram sebelum Larasati seperti Tetralogi Bumi
Manusia, kita tentu akan mengenali Pram dengan penulis yang karya-karyanya
dapat dibedah dengan teori ini. Masih sama dengan Larasati, Pram tetap
menggunakan latar waktu ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Menariknya,
Pram selalu memiliki ‘gadis’nya masing-masing dalam setiap karyanya. Dalam novel
inipun, Larasati merupakan tokoh utama. Pram mencoba memotret kondisi relasi
antara penjajah dan terjajah dari sudut pandang seorang perempuan bernama
Larasati.
Dalam
Larasati, kedatangan Belanda untuk
kedua kalinya ke Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa betapa kuatnya bangsa
Barat. Sebagai bentuk dari superioritas bangsa Barat, kedatangan kembali
Belanda ke Indonesia merupakan sebuah ancama terbesar bagi negara yang baru
saja merdeka. Keadaan pemerintahan yang saat itu baru saja terbentuk tentu masih
carut marut. Belum terbentuknya pemerintahan yang kuat di Indonesia, membuat
Belanda terlampau mudah untuk kembali menguasai Indonesia.
Kedatangan
kembali Belanda akhirnya memberikan pengaruh bagi rakyat Indonesia sendiri.
Belanda menjadi sebuah negara kolonial yang benar-benar tidak dapat dipandang
remeh. Dalam novel ini, Pram mengisahkan dua tokoh orang Indonesia yang
terpengaruh atas kekuatan Belanda dan memilih untuk berpihak kepada Belanda.
Tokoh pertama ialah Kolonel Surjo Sentono, seorang kolonel inlander yang
berasal dari yang berasal dari Indonesia dan berpihak pada NICA.
“Kehormatan mana lagi
yang mesti kau pertahankan?”Kembali airmata membahasi matanya yang baru
sebentar tadi kering. Tetapi Larasati tahu, terhadap pengkhianat-pengkhianat ini
tak perlu mengalah, ia pun tak akan pernah. Dan perlahan-lahan ia menjawab,
“Memang aku hanya seorang pelacur, tuan kolonel. Tapi aku masih berhak
mempunyai kehormatan. Karena kau tidak pernah menjual warisan nenekmoyang pada
orang asing.”
Seperti
yang dibahasa dalam paragraf sebelumnya, Belanda bukanlah bangsa kolonial yang
dapat dipandang sebelah mata. Kedatangan Belanda untuk kedua kalinya akhirnya
menunjukkan bahwa bangsa Timur merupakan bangsa yang inferior. Sifat yang
menjadi ciri khas dari bangsa Barat inilah pada akhirnya ikut mempengaruhi
pemikiran dari Kolonel Surjo. Ia tidak segan memposisikan dirinya sebagai
superior walaupun ia hanya seorang Indonesia yang berpihak kepada Belanda.
“Main sandiwara?” kolonel inlander itu
batuk-batuk kecil, tapi kemudian suaranya bernada ancaman., “Ah, tidak. Seorang
replubikein tidak bisa bermain sandiwara dengan tepat.”
Kalimatnya
tersebut seakan seperti sedang memperolok Larasati yang terang-terangan
menyatakan bahwa ia seorang republikein. Walaupun kolonel tersebut berbicara
pada dirinya sendiri, kata “republikein” merupakan kata yang ditujukan kepada
Larasati setelah Larasati menyatakan ia tidak ingin bergabung dengan NICA. Kata
‘republikein’ mengacu kepada orang Indonesia, bangsa Timur yang inferior. Dalam
kalimat ini, Kolonel Surjo Sentono juga menunjukkan bahwa seorang republikein yang
inferior tentu tidak dapat melakukan suatu hal yang benar berbeda dengan bangsa
Barat yang menguasai ilmu pengetahuan.
Keberpihakannya
kepada Belanda membuat Kolonel Surjo memiliki cara berpikir dan cara pandang
yang sama dengan Belanda. Cara berpikir dan cara pandang inilah yang akhirnya
membuatnya merasa bahwa ia setara kedudukannya dengan Belanda. Sehingga ia
berhak memperolok bahkan merendahkan orang Indonesia. Selain merendahkan dengan
mengakatakan seorang republikein tidak dapat melakukan sandiwara dengan tepat,
Kolonel Surjo juga memberikan sebutan yang tidak pantas terhadap republikein
sendiri sama dengan sebutan Belanda kepada para kaum terjajah.
“Antarkan dia, aku bilang!”
“Penjara mana, tuan kolonel?”
“Husy, kau tahu di mana
monyet-monyet itu dikurung, pergi!”
Kata
‘monyet-monyet’ yang disebutkan oleh seorang Kolonel Surjo tersebut ditujukan
bagi para pejuang-pejuang yang tertangkap oleh Belanda kemudian dipenjarakan.
Dengan menggunakan kata ‘monyet’ sebagai sebutan bagi para pejuang Indonesia
telah menunjukkan bagaimana Kolonel Surjo beranggapan bahwa ia berhak memiliki
sikap yang sama dengan Belanda walaupun ia sendiri adalah orang Indonesia. Hal
ini dikarenakan keberpihakann ya kepada Belanda sehingga ia menganggap dirinya
sejajar dengan kolonial sehingga berhak memperlakukan pejuang Indonesia atau
republikein lainnya sama dengan cara Belanda.
Indonesia
yang kala itu baru saja berdiri sebagai negara baru, tentu masihlah menata
pemerintahannya. Persenjataan untuk keamanan negara sendiri pun masihlah kalah
dengan para kolonial. Barat yang menjadi pusat pengetahuan tentu memiliki
perkembangan persenjataan yang jauh lebih mutakhir daripada Timur. Hal ini pula
yang menjadikan Barat turut berbangga dan merasa pantas untuk menjadi bangsa
yang superior.
Pada
tokoh kedua terdapat Mardjohan, seorang announcer
serta produser film. Keberpihakkan Mardjohan terhadap Belanda dikarenakan
kebenciannya terhadap revolusi yang memisahkannya dari gadis yang ia cintai.
Kebenciannya itulah yang akhirnya membuat ia mengikuti jejak dari Kolonel Surjo
Sentono berpihak kepada Belanda. Lama bergaul dengan Belanda akhirnya
menciptakan pemikirannya yang sama yakni superior. Mardjohan menganggap,
kemenangan dalam suatu perang dapat dilihat dari persenjataan yang mutakhir.
“Kau begitu yakin pada
kemenangan Revolusi. Aku lebih percaya pada kemenangan meriam.”
Pernyataan
yang diberikan Mardjohan kepada Ara, menunjukkan bahwa bagi Mardjohan revolusi
hanyalah sebuah perlawanan tanpa arti. Perlawanan sesungguhnya adalah negara
yang memiliki senjata yang modern, yakni meriam. Kekuatan senjata Belanda
membuat Mardjohan tertarik daripada sekedar melawan dengan semangat revolusi.
Kesimpulan
Sebagai
sebuah negara yang baru saja merdeka kemudian didatangi kembali oleh sebuah
negara yang pernah menjadi penjajah di Indonesia, tentu bukanlah hal yang
mudah. Mengingat sistem pemerintahan masihlah baru dan belum terlalu kuat.
Kedatangan Belanda ini pada akhirnya tidak dapat dipandang remeh sehingga
mempengaruhi beberapa orang Indonesia untuk berbalik berpihak kepada Belanda.
Novel yang sarat dengan mimikri pada kedua tokoh yakni Kolonel Surjo Sentono
dan Mardjohan, merupakan sebuah pembuktikan bagaimana kolonial memiliki
pengaruh yang begitu besar bahkan hingga ke psikis seseorang.
Daftar Pustaka
Teeuw, A. 1983. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia Pustaka
Yasa, I Nyoman. 2012. Teori Sastra dan Penerapannya. Bandung:
Karya Putra Darmawati
Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif
Klasik, Modern, Postmodern, dan poskolonial. Jakarta, Rajawali Post
Ratna, Nyoman Kutha. 2008. Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Toer, Pramoedya Ananta. 2009. Larasati. Jakarta: Lentera Dipantara



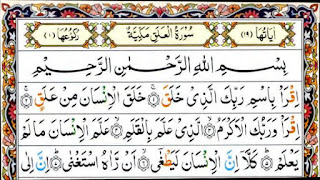
Komentar
Posting Komentar